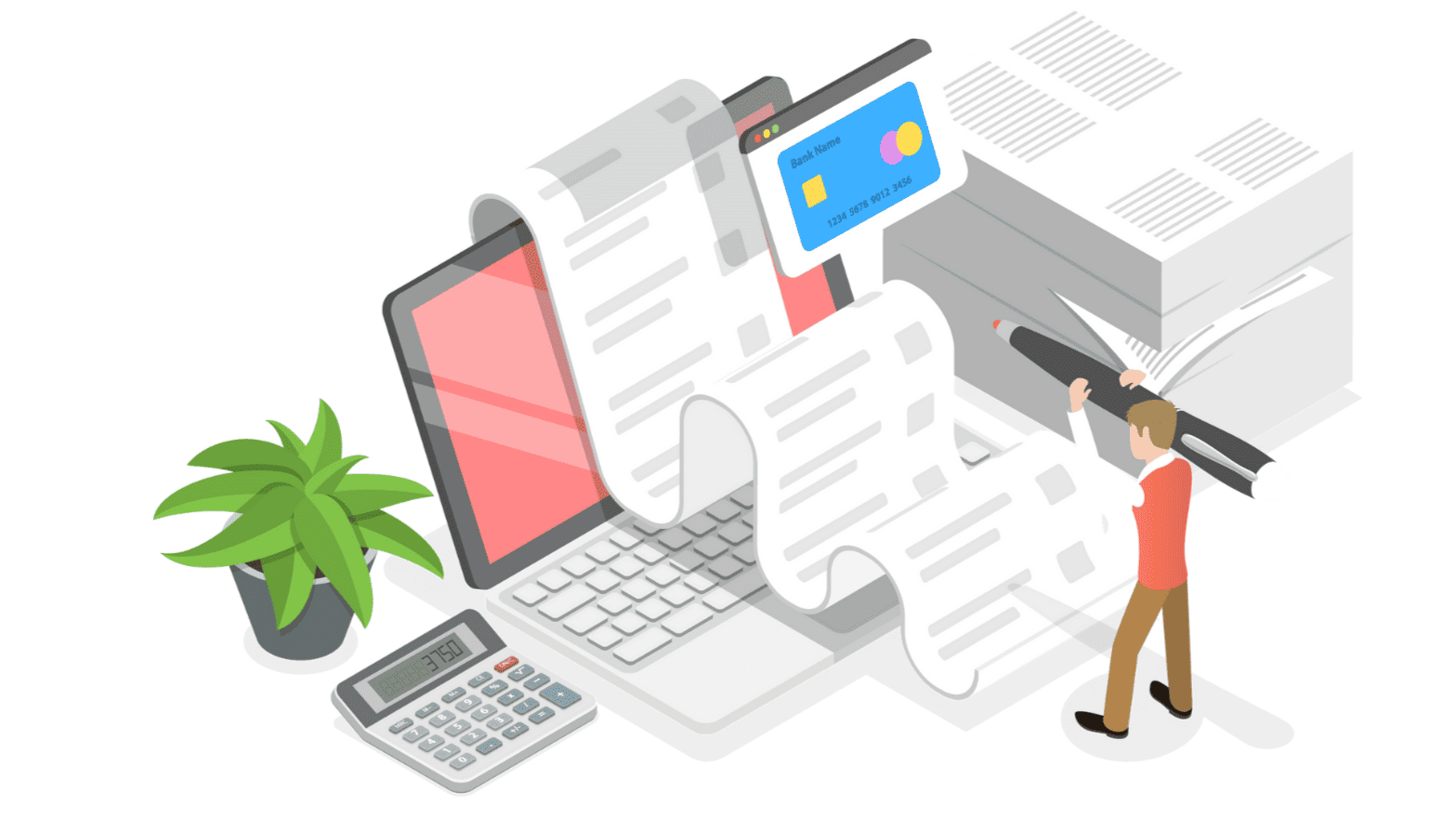Remang
Selasa, 16 November 2021 17:01 WIB
Fiksi
Menyusuri jalan ini hanya mengingatkanku kepadamu. Hawa Jakarta masih panas, pengap seperti biasanya. Bunyi klakson kendaraan roda dua menjadi hiasan kisah kita, aku masih ingat itu. Sebentar lagi sampai, aku harus bertahan. Hanya beberapa menit lagi, siluet panjang bayangan pohon palem seolah memotong trotoar, tak membuatku gentar—walau tampak sedikit menakutkan. Cahaya kuning dari lampu jalanan membuat suram petang ini. Tunggu aku, Aulia, tunggu aku.
Semakin aku menyebut namanya dalam hati, semakin lebar pula langkahku. Belokan kafe tempat kita janjian sudah di depan mata, tinggal beberapa langkah lagi aku akan menjumpaimu.
Tidak ada suara apa pun terdengar dari luar. Aku sudah di depan jendela kafe. Sepanjang mata memandang, temaram yang terlihat. Di mana kamu, Aulia? Deretan meja kayu bundar dan kursi besi tempa berwarna hitam membuat keteduhan yang tak bisa kumengerti.
Aku tersenyum, berapa kali kita ke sini? Tak terhitung, kan? Sudah sejak lama, kan? Mungkin sejak seragam kita abu-abu, lalu jaket almamater, lalu....
Pintu bergerak terbuka, denting lonceng kecil terdengar. Secepat orang itu keluar, aku masuk. Aku rasa jantungku berdegub kencang, Aulia. Wangi aroma eskrim menguar di ruangan yang cukup luas ini. Aku sangat hapal kesukaanmu, Aulia. Dua scoop Rhum Raisin dan cukup satu scoop Green Tea, akan membuatmu betah menatap mangkok beling di hadapanmu. Ah, terkadang aku cemburu, Aulia, pada gelas itu, pada eskrim yang menyentuh bibir merahmu.
Kamu akan menepati janjimu, kan? Kamu akan datang, kan? Pasti kamu akan datang, demi bertahun-tahun pertemanan kita. Kamu tidak akan melupakannya, kan? Demi hatiku, Aulia.
Dua orang pelayan mondar-mandir. Nampan di tangannya seperti merekat erat di telapak tangan mereka. Sungguh, itu tidak mudah dilakukan. Aku pernah mencobanya, berakhir dengan pecahnya dua gelas dan teriakan kagetmu; Bagas! Awas! Pecah, kan?!?
Was-wasmu menyenangkanku. Sungguh, ingin kupecahkan seluruh isi lemari kafe ini.
“Selamat malam, Sobat. Malam ini kami hadir kembali untuk menghibur, hingga dua jam ke depan.”
Sapaan vokalis band indie membuatku menggeser tempat duduk agar bisa lebih jelas lagi melihat penampilan mereka. Nomor meja bertuliskan angka 15 seperti menghalangi pandanganku, tidak sabar aku merebahkan benda itu asal, membuat tusuk gigi yang ada di bagian bawah acrilyc tercecer di atas meja. Kalau ada Aulia, dia akan memungutinya satu per satu, dengan omelan tanpa henti dari mulutnya. Oh ya, mata kejoramu, ah, mata bola pingpongmu itu, melotot. Alis indahmu melengkung. Boleh aku mengecupnya, Aulia?
Selain eskrim, live music juga yang membuat aku dan Aulia berbetah-betah di sini.
“Seperti biasa, permintaan lagu-lagu akan kami layani.”
Aku mengacungkan tangan setinggi mungkin, aku mau meminta lagu, sebelum Aulia datang. Aku yakin, sangat yakin, aku yang pertama kali mengacungkan tangan. Tapi pelayan pencatat lagu-lagu permintaan hanya melengos ke arahku, melewatiku begitu saja. Sialan!
“Aku mau lagu lama, boleh, Mas?” suara perempuan terdengar dari meja di sebelah kananku. Aku mencibir dalam hati, pasti orang baru. Tidak tahukah mereka semua, nyaris semua lagu dari segala dekade bisa dinyanyikan oleh grup band luar biasa ini.
Aku menunggu dengan sabar, biarlah, toh Aulia belum datang.
Sebuah lagu lama terdengar. Ya ya ya, okelah, lagunya enak di kuping. Lagu-lagu berikutnya dilanjutkan, request berikutnya setelah beberapa lagu selesai. Nanti aku tidak boleh kalah.
“Mau tambah minum apa, Mas?” Suara pelayan terdengar dari belakang. Membuatku pura-pura menggeliat, aku hanya mengurangi kesempatan rasa bosan menghampiri. Sepasang anak manusia ada di meja itu, mereka menunjuk daftar menu, kemudian dicatat dengan tekun oleh sang pramusaji.
Aku juga ingin memesan minuman, biarlah nanti Aulia yang memesan makanannya. Aku menunggu pelayan itu selesai mencatat.
“Hei, Mas, sa—”
Belum selesai aku memanggilnya, dia hanya melewatiku begitu saja. Kurang ajar juga lama-lama nih orang!
Aku berdiri, paling tidak satu dua tonjokan atau gertakan, mungkin bisa membuat pelayan itu sadar kehadiranku. Tanganku hampir meraih kerah kaosnya ketika wajah Aulia terbayang, wanitaku itu pernah berkata, “Aku tidak suka kamu berkelahi, Bagas.” Perkataannya adalah sabda bagiku.
Aku menarik napas dalam. Baiklah, aku mengalah padamu kali ini, Cuk!
Lagu-lagu mengalun tanpa henti. Entah berapa kali aku menengok pintu masuk. Aulia belum datang juga.
Tapi jangankan hitungan jam, berhari-hari pun akan kutunggu dirimu, Aulia. Jangan pernah meragukan kesabaranku, atasmu. Kalau pujangga lama masih hidup saat ini, berapa banyak ode akan tercipta karena kegigihanku.
Jangan kamu mengira aku meragukan dirimu, Aulia, tapi bolehkah aku bertanya untuk pertama kali, akankah dirimu datang malam ini?
Aku mengetuk meja, mengikuti alunan musik. Sejenak irama riangnya membuatku lupa waktu, tepuk tangan pengunjung menutup penampilan mereka di setengah penampilan mereka malam ini. Ruangan kembali sunyi, mungkin untuk sepuluh menit ke depan. Bisik-bisik pengunjung mulai terdengar sayup-sayup. Denting garpu beradu dengan piring pun terdengar.
Tiba-tiba...
Kling!
Bunyi jernih lonceng kecil terdengar. Kali ini aku pasti tidak salah.
AULIA! Dia datang! Dia datang!
Oh Tuhan, aku yakin Engkau menciptakan manusia perempuan ini saat Engkau sedang bahagia. Sama seperti biasanya, Aulia-ku mempesona. Rambutnya masih panjang, menjuntai tanpa jepit rambut atau apalah namanya, yang biasa dia pakai di rambutnya. Bajunya...kamu memakainya, Aulia! Itu adalah hadiah dariku, kan? Aku yang memilihnya, untukmu, walaupun kamu berkata harus mengecilkan pingang dan panjangnya beberapa senti. Ah, berbuatlah sesukamu, Aulia, apa pun, asal kamu senang.
Di sini, Aulia! Di sini! Panggilku sekencang aku bisa melakukannya, masa bodoh dengan orang-orang yang merasa terganggu.
Dia menatapku dari kejauhan, kami bertatapan, lama. Aku tersenyum padanya.
Tahukah kamu, Aulia, malam ini adalah saatnya. Malam ini aku hendak menyatakannya. Aku akan mengungkap semua isi di hati, agar kamu tahu Aulia, akulah laki-lakimu satu-satunya untuk selamanya. Aku akan menyatakan rasa cintaku padamu, Aulia.
Aulia menghampiri sudut eskrim. Dari kejauhan aku tahu apa yang dipesannya. Dia berjalan anggun dengan eskrim di tangan, menuju arahku.
Ke sini! Teriakku.
“Mbak Aulia? Udah lama nggak kemari,” sapa seseorang. Aku menjulurkan leher dan menyipitkan mata, berusaha mengenali sosok dalam sudut gelap ruangan. Siapa dia? Ah, ternyata Mas Bowo, pemilik kafe ini. Mereka mengobrol cukup lama, Aulia terlihat santai, sesekali menikmati eskrimya.
Cepatlah kembali ke kantormu di atas, Bangsat! Makiku. Ini adalah malamku, tidak ada yang boleh mengganggu. Tidak juga kamu!
Lalu aku merasa lega saat Aulia terlihat menjauh dari predator itu.
Aku tersenyum lebar, dan kurasa Aulia juga tersenyum. Tapi mengapa dia terlihat bingung? Celingukan seolah sedang mencari sesuatu. Kehilangan sesuatukah? Aku turut menatap sekeliling mengikuti gerakan matanya.
Di sini, Aulia, di—
Kurasa dia mendengar teriakanku. Dia menarik kursi di depanku. Baiklah, tidak apa-apa dengan pilihan tempat dudukmu, yang penting aku bisa melihatmu dengan jelas.
Apa kabar, Aulia? Tanyaku padanya, dia hanya tersenyum, mungkin lelah. Aku tersenyum juga. Tetapi senyumku hanya untuk meredakan debar jantungku yang tak menentu.
Aulia, aku—
“Oke! Kita lanjutkan ya! Yang mau meminta lagu silakan!”
Aulia melanjutkan menikmati eskrimya, aku memutuskan untuk membiarkannya dulu. Mungkin tiga puluh menit saja, aku butuh waktu sedikit lebih banyak untuk bicara.
Lantunan lagu sedih terdengar. Entah siapa yang memesan lagu itu, aku hanya bisa diam di depannya saat ini. Begitu berbeda dengan malam-malam sebelum ini, saat canda tawa menjadi ikon setiap pertemuanku dengannya.
Lagu kedua mengalun, aku masih juga diam. Ke mana larinyta nyali yang tadinya berkoar-koar perkasa.
Lagu ketiga, eskrimmu sudah habis sama sekali, kamu hanya menopang dagu dan sesekali memainkan sendok es.
“Ada satu permintaan lagu, dari Pak Bos, katanya untuk Aulia yang duduk di sana....” suara vokalis kali ini membuatku dan Aulia mendongak bersamaan.
Bunyi gitar akustik terdengar indah. Menyihir semua orang terutama aku dan Aulia-ku.
Tiga puluh menit kita di sini, tanpa suara
Dan aku resah harus menunggu lama, kata darimu.
Mungkin butuh kursus, merangkai kata, untuk bicara
Dan aku benci harus jujur padamu, tentang semua ini.
Jam dinding pun tertawa, karna ku hanya diam, dan membisu.
Ingin kumaki diriku sendiri, yang tak berkutik di depanmu.
Ada yang lain di senyummu, yang membuat lidahku gugup tak bergerak
Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri, tuk bilang...Aku sayang padamu....
Itu...itu laguku! Itu adalah lagu kesukaan Aulia!
Denting gitar mengalun merdu, pelan, dan...Aulia mulai terisak.
Mengapa menangis, Aulia? Mengapa? Jangan khawatir, Aulia. Aku akan menyatakannya padamu sekarang. Aku mencintaimu, Aulia! AKU MENCINTAIMU!!!
Aulia masih tersedu, pundaknya bergetar. Ini membuatku pilu, hatiku teriris sembilu, sakit. Jangan menangis, Sayang, aku akan selamanya mendampingimu.
“Mbak Aulia, kenapa?”
Sosok Mas Bowo tiba-tiba ada di samping Aulia. Aku melotot tidak suka. Hatiku membara! Dia milikku! Aku cemburu!
Tanpa mempedulikan apa-apa lagi, aku berdiri, menghampiri laki-laki tidak sopan itu dan menghantam tepat di wajahnya dengan kepalan tanganku. JANGAN DEKATI AULIA! Bentakku kencang.
Tapi... tapi...mengapa....
Aku terbelalak, apa yang kulihat di hadapanku membuatku terhuyung, hampir jatuh. Mengapa aku tidak bisa memukul orang itu??? Aku....
Sekali lagi aku mendekat, berusaha memukul kepalanya. Tapi sekali lagi hanya angin yang terkena. Aku terhuyung lagi.
Menatap tanganku tak percaya. Apa yang terjadi padaku???
AULIA! Teriakku, tetapi tak sekejap pun Aulia mengangkat wajahnya. Malah Mas Bowo mengusap pipi Aulia-ku dengan punggung tangannya.
TIDAKKK!!!
Aku tertatih, mendekati mereka berdua, aku berusaha menyentuh bahu Aulia, namun sekali lagi hanya angin yang terasa. Oh Tuhan....
Aku terduduk jatuh di lantai, di kaki Aulia. Menatapnya kosong.
“Saya tahu, hari ini kamu pasti ke sini, seperti tahun-tahun yang lalu....” kata Mas Bowo.
“Saya...belum bisa melupakan Bagas, Mas. Saya...kangen, Bagas,” ucap Aulia lirih.
Aku juga merindukanmu, Aulia. Aku mencicit, merintih dalam perih.
“Saya mengerti...makanya saya pesan lagu ini buat kamu.”
“Bagas selalu pesan lagu ini untuk saya, Mas. Tiga tahun lalu, Bagas meminta saya datang ke sini, katanya ada yang mau dia bicarakan. Dia bilang agar menunggunya di meja nomor lima belas...”
Aku meraung sekeras-kerasnya! Aku sudah di sini, Aulia!
“Meja nomor lima belas habis terbakar karena ledakan gas saat itu. Tidak ada lagi meja nomor lima belas setelah tempat ini direnovasi.”
Aku menatap Aulia nanar. Aku rasa aku mulai ingat apa yang terjadi tiga tahun lalu. Aku tergugu, menangis seperti anak kecil.
Aulia....
“Kamu tahu apa yang mau dibicarakan sama Bagas?”
Aulia mengangguk, “Saya tahu, Mas, saya tahu....” Isaknya mulai terdengar lagi. Aku menatapnya lekat, sendu merasukiku. Tangan Aulia saling berpilin, aku tahu emosinya terkuras.
Dia menarik napas panjang lalu mengembuskannya perlahan.
Setengah berbisik, dia berkata—seolah aku ada di hadapannya, “Aku juga mencintaimu, Bagas....”
Aku tersenyum, ada kelegaan luar biasa dalam hati. Akhirnya aku mendengar dari mulut Aulia sendiri. Tubuhku terasa begitu enteng, beban yang tadinya begitu sesak, kini hilang sudah.
Aku berdiri, ada yang menuntunku untuk berdiri. Saatnya sudah tiba. Aku harus pergi.
Selamat tinggal, Aulia. Aku mencintaimu....
Ada yang menuntunku, berjalan menjauh, menuju sinar terang benderang di kejauhan.
***
Tiga tahun lalu.
“Woy, Aul, ke kafe, yuk!” Bagas menggandeng lengan Aulia di luar pagar kampus.
“Ngapain, baru dua hari lalu ke sana.”
“Ayolah, pokoknya penting deh!” seru Bagas, sembari mengacak rambut Aulia.
Aulia berteriak kesal, karena dia sudah bermenit-menit menghabiskan waktu untuk menata rambutnya pagi tadi.
“Apaan?? Mau nembak si Wina??” Aulia bersungut-sungut. Ada rasa tidak suka menyelinap.
“Tau aja...” ledek Bagas. Aulia mendorong badan Bagas sekuat tenaga, membuat laki-laki kerempeng itu terjatuh. Tasnya ikut terjatuh dan membuat sebagian barangnya tercecer.
Bagas tertawa, dengan sigap berdiri setelah dengan asal mengambil barang-barangnya dan memasukkannya kembali ke dalam tas.
“Cari aku di meja nomor lima belas, nanti malam jam tujuh, oke? Sekarang aku ke rumah Ferry dulu, ambil tugas, dadah!”
Aulia mengentakkan kakinya, setengah kesal. Namun senyum tersungging juga di bibirnya, memandang punggung Bagas, laki-laki yang sudah menemaninya selama enam tahun. Ketika dia hendak beranjak pergi, matanya melihat sepotong kertas berwarna hijau berbentuk hati dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya, tulisan tangan Bagas.
I love you, Aulia.
Wajahnya memerah seketika. Dadanya seolah menabuhkan genderang, bertalu-talu. Tak sabar dia menunggu malam tiba.
Beberapa jam kemudian, dia sudah berada di dalam bis menuju kafe tempat Bagas akan menemuinya. Senyum tak lepas dari bibirnya.
Semakin dekat, jantungnya seolah memainkan marching band meriah.
Ketika bis berhenti di halte, dia buru-buru turun dan setengah berlari menuju ujung jalan. Tiga menit kemudian, dia menghentikan langkahnya tiba-tiba. Kerumunan orang-orang memenuhi jalanan. Bunyi sirine mobil kebakaran semakin lama semakin keras terdengar.
Aulia menatap panik, dia berusaha membelah kerumunan. Kafe tempat dia akan bertemu dengan Bagas terbakar!
“MINGGIR! MINGGIR! ADA KORBAN MENINGGAL!”
Dua orang tampak membawa tandu dengan sosok manusia di atasnya. Aulia tercekat, hatinya berdebar untuk alasan yang berbeda kali ini. Dia mendekati tandu, mulai mengenali lengan yang terjuntai keluar dari kain yang menutupi. Tangannya bergetar saat menyingkap kain itu.
“BAGASSSS!!!”
Tamat
Penulis Indonesiana
0 Pengikut
Baca Juga
Artikel Terpopuler


 0
0
 Berita Pilihan
Berita Pilihan

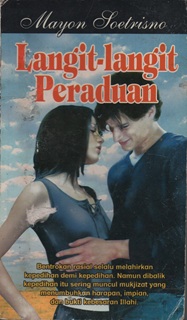






 97
97 0
0